Sebuah Perjalanan Waktu untuk Menyelami Diri
Jika suatu saat aku bertemu kembali dengan diriku di 10 tahun yang lalu, aku pasti akan mengguncang bahunya dan berkata, “Hei, percayakah jika kamu ternyata dapat bertahan sampai umurmu 24 tahun? Bahkan lebih bahagia dari apapun?”.
 |
| (Sumber: karya pribadi) |
Akan kukatakan pada diriku sendiri dari masa lalu bahwa hidup
tidak seburuk yang pernah kami kira, bahwa kesialan memang tidak bisa dicegah,
namun juga bahwa kebahagiaan tidak melulu berlangsung sementara. Bahagia itu
relatif, dan bagaimana kita mempersepsikan kebahagian itulah yang bertindak
sebagai jam pasirnya.
Melihat
kembali kehidupan yang sudah berlalu, tidak terasa ternyata aku sudah berjalan
di bumi ini selama itu. Pahit getir kehidupan, manis bahagia, bahkan kemotonan
menghampiri kehidupanku satu persatu tanpa luput memunculkan emosi-emosi yang
sama sekali berbeda dari sebelumnya. Diriku yang lama mungkin akan mengutuk
berbagai emosi tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang acak dan terus
menerus terjadi tanpa dapat dihentikan. Diriku yang lama pasti membenci itu,
karena perubahan bukanlah teman terdekatku saat itu.
Oh iya,
selain perubahan, diriku yang lama juga membenci diriku sendiri.
Ada
banyak sekali kebencian saat itu hingga rasanya menyesakkan. Diriku yang lama
selalu berdoa agar hidupnya berakhir sebelum menyentuh angka 25. Diriku yang
lama akan menghindar ketika orang-orang bertanya mengenai kabarnya. Diriku yang
lama akan senang sekali memupuk kebencian terhadap berbagai aspek di dunia.
Saat kini aku kembali menekuri semua itu di usiaku yang sekarang, aku hanya
ingin memeluk diriku yang lama. Betapa kebencian terhadap kehidupan sudah
membuat dirinya jauh terpuruk dan melupakan bahwa ada banyak hal yang berharga
dalam hidup yang belum ia sadari.
Bukan
berarti aku sepenuhnya dapat berhenti membenci diriku. Tapi setidaknya
sekarang, aku mencoba berdamai dengannya. Mencoba menerima bagian-bagian yang
tidak kusukai, menganggapnya seperti anggota tubuhku sendiri yang tidak mungkin
bisa dilepas. Belajar untuk terus hidup beriringan, bersama segala kelemahanku.
Benar-benar menerima.
Ayahku
selalu mengatakan bahwa sejak kecil, aku adalah gadisnya yang paling tempramen.
Wajahku lebih banyak tertekuk karena merengut daripada tersenyum. Aku adalah
anaknya yang paling mudah terpicu emosinya. Saat bersama dengan keluarga besar
yang lain, aku lebih sering diam dan duduk menyendiri. Kurasa saat itu mungkin
aku juga mengeluarkan aura tidak menyenangkan pada semua orang. Saat itu,
kupikir bibi dan pamanku bahkan tidak menyukai keberadaanku karena mereka
jarang sekali menyapa. Benar-benar anak yang sulit sekali untuk diajak bicara.
Ibu juga
menganggap demikian. Bagi beliau aku adalah anak yang paling sulit untuk diajak
berkompromi. Karena ketika aku tidak setuju pada suatu hal, maka aku akan
bersikap keras kepala dan memilih bungkam. Aku paling sulit dipaksa, meski itu
untuk kebaikan diriku sendiri. Tidak hanya sekali Ibu akhirnya menangis akibat
kekeraskepalaanku. Terkadang beliau sampai memohon agar aku mengerti lalu setuju
pada apapun yang beliau tawarkan saat itu, tapi sudah kubilang bahwa aku ini
keras kepala. Aku lebih memilih diam daripada mengatakan apapun pada Ibu.
Aku
pernah sampai pada tahap membenci Ibuku sendiri. Sampai pada tahap bahwa aku
tidak tahan untuk hidup satu atap dengan kedua orang tuaku. Saat itu mungkin
umurku sekitar 13 tahun. Diriku yang sekarang meringis mengingat kenangan itu.
Betapa sikapku yang keras kepala justru membangun tembok antara diriku dan
keluargaku sendiri.
Aku tidak
ingin membela diri. Tapi kupikir aku punya alasan mengapa dulu aku bersikap
demikian. Diriku yang berumur 13 tahun merasa bahwa semua itu sudah tidak
tertahankan, meski diriku yang berumur 24 tahun justru merasa bahwa
pengalaman-pengalaman tersebut memang pantas untuk kulalui. Bahwa dengan semua
pengalaman tidak menyenangkan itu, aku dapat tumbuh seperti sekarang. Bukan
bijaksana, belum. Tapi setidaknya untuk memahami makna pada tiap kejadian.
Aku
adalah anak sulung dari 3 bersaudari. Aku tumbuh sejak perekonomian keluargaku
belum stabil hingga pada akhirnya kami dapat hidup berkecukupan saat ini. Jarak
umurku dengan adik-adikku adalah sekitar 5 dan 10 tahun. Sejak kecil, aku
menginginkan banyak hal seperi layaknya anak-anak lain seusiaku. Namun seringnya aku tidak berkesempatan mendapatkan semua itu. Bukan karena saat itu
aku sadar mengenai kondisi finansial keluargaku, bukan, melainkan karena aku
takut.
Ya, aku
takut. Kepada orang tuaku.
Dulu,
dimulai sejak aku berada di taman kanak-kanak, Ayah terbiasa memarahiku dengan
sesekali menghukumku secara fisik jika aku bersikap nakal. Seringnya berupa
pukulan dan tendangan. Beberapa kali aku mendapat hukuman dikurung di kamar
mandi. Aku ingat aku menangis kencang sekali, tapi justru dihadiahi dengan
lebih banyak pukulan. Jika masih menangis, Ayah akan mengancam mengurungku. Pernah
suatu kali, kakiku diikat karena aku terlambat pulang dari bermain. Ayah marah
sekali. Aku ingat mataku saat itu mencoba untuk mencari Ibu, meminta
pertolongan padanya, meminta perlindungan dari Ayahku.
Namun,
ketika aku berlari sambil menangis pada Ibu, beliau justru membentakku.
Mengatakan bahwa aku harusnya mendengarkan Ayah dan berhenti menangis. Aku
tidak tahu apakah anak kecil berumur 5 tahun dapat merasakan patah hati, tapi
saat itu aku benar-benar merasa remuk. Pada akhirnya kakiku diikat dan aku
ditinggal sendirian di ruang tamu. Sambil menangis, aku mengesot sambil mencari
gunting, berusaha membebaskan kakiku sendiri. Setelah bebas, aku cuma bisa
menangis sendirian di kamar.
Kini aku hanya dapat mengingat kejadian itu
dengan getir. Fakta bahwa pengalaman itu tidak pernah hilang dari benakku
menjadi bukti kalau luka yang ditorehkan begitu dalam.
Adik
pertamaku lahir saat aku berumur 6 tahun. Aku senang sekali karena akhirnya aku
punya teman baru. Adikku sangat lucu dan cantik. Aku sangat menyayanginya,
begitu pula orang tuaku. Perhatian mereka sepenuhnya tercurah pada adikku. Aku
tidak marah, karena
aku menyayangi adikku dan aku bangga terhadap statusku sebagai kakak. Aku mulai
tidak banyak meminta, aku selalu ingin membantu Ibu mengurus adikku. Aku
menyanyikan nina bobo, tidur bersama adikku, mengajaknya berbicara, belajar
mengganti popoknya, memberi makan bubur setiap kali ia lapar dan membuatkan
susu ketika ia haus. Orang tuaku mulai jarang memarahiku dan aku senang atas
itu.
Lalu adik
keduaku lahir saat aku berumur 11 tahun. Lagi-lagi bayi perempuan yang lucu dan
tembam. Adikku yang kedua juga sangat cantik. Sama seperti adikku yang pertama,
aku juga merawatnya dengan suka cita. Aku menggendongnya, mengajaknya bermain
bersama dengan adik pertamaku. Aku merasa sebagai kakak yang paling bahagia.
Sampai
suatu ketika, tanganku agak meleset saat menggendongnya di atas kursi dan
adikku terjatuh ke lantai. Suara benturan kepalanya dengan lantai sangat
kencang, aku sangat panik adikku akan terluka. Saat itu, usianya mungkin baru 2
tahun. Ia menangis kencang, orang tuaku datang dan memarahiku. Ibu merenggut
adik dari tanganku, lalu Ayah menarikku hingga berdiri dan memukulku.
Aku
menangis, merasa tidak adil. Saat itu aku hanya ingin membuat adikku tertawa.
Aku merasa bersalah, aku menyadari kelalaianku dan aku menyesal. Namun ketika
aku ingin bicara, baik Ibu dan Ayah justru
mengomeliku. Saat itu ada paman dan bibi yang menyaksikan. Aku ingat sekali
bagaimana cara mereka memandangku, dan aku ingat merasa sangat sakit hati saat
menyadari bahwa mereka takkan membelaku.
Untuk
pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar terkucilkan dari keluargaku
sendiri. Di umurku yang ke-13 aku merasa diperlakukan tidak adil.
Ayah dan Ibu
juga selalu melarangku melakukan apapun yang menurut mereka tidak ada gunanya.
Aku tidak diperbolehkan menghadiri acara ulang tahun temanku, aku tidak boleh
bermain terlalu lama, aku tidak boleh bermain terlalu jauh, dan banyak larangan
lainnya. Sepanjang pertumbuhanku, segala keputusan selalu diambil oleh Ayah dan
Ibu. Mereka tidak pernah mengizinkanku mengambil keputusanku sendiri.
Karena
terbiasa diperlakukan seperti itu oleh orang tuaku, aku tumbuh menjadi anak
yang penakut dan sulit untuk berbaur dengan anak-anak lain. Aku belajar untuk
mengunci suaraku dan mengurung perasaanku jauh di dalam hati karena tidak ingin
dipukul dan dimarahi. Berdebat tidak ada gunanya, karena ketika aku mencoba
untuk menyuarakan pendapatku, sekejap mata orang tuaku akan memotongnya. Aku
tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara. Bahkan hanya untuk membela
diriku sendiri pun tidak bisa. Aku menjadi tidak percaya diri.
Di umur
13 tahun, aku belajar untuk mengalah dan membangun tembok dengan orang tuaku
sendiri. Aku menemukan hobi membaca saat itu, maka aku lebih memilih untuk
menghabiskan waktu dengan membaca di kamar sendirian. Jauh dari masalah. Aku
berhenti bicara pada Ibuku, hanya bicara ketika perlu saja. Sisanya aku akan
berjalan ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Namun ternyata, sikapku yang
seperti itu justru membuat orang tuaku semakin tidak suka. Mereka pernah
mengancam akan membakar buku-bukuku apabila aku terus seperti itu. Mereka sudah
pernah membakar koleksi binderku saat aku masih kecil, jadi aku percaya dengan
ancaman mereka.
Sekarang,
di umur 24 tahun, aku menyadari alasan mengapa aku sangat mudah terpicu
emosinya namun sulit untuk mengungkapkannya. Aku hanya bisa menunjukkannya
lewat ekspresi, namun takkan pernah bisa menyuarakannya dalam kata-kata. Aku
tidak terbiasa untuk itu, orang tuaku mendidikku agar tidak banyak protes.
Lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi?
Kelekatan yang terbentuk antara diriku dengan
orang tua bukanlah tipe kelekatan yang baik. Ketika kelekatan harusnya dapat
mendorong hubungan antara anak dan orang tua menjadi lebih baik, menjanjikan
rasa aman dan terlindungi bagi anak (Agerup et al., 2015). Hal tersebut tidak terjadi dalam perkembanganku. Alih-alih mengembangkan
kelekatan yang aman (secure attachment), masa kecilku diisi oleh
kelekatan yang minim dan dipenuhi oleh perasaan tidak aman (insecure
attachement).
Saat menilik lagi ke masa lalu, aku mengingat
bahwa diriku di masa lalu mulai cenderung menunjukkan gejala-gejala yang
mengarah pada gangguan depresi. Meski saat itu, aku tidak mengerti betul apa
yang kurasakan, yang kutahu hanya perasaan sedih berkepanjangan yang tidak
pernah hilang sepenuhnya.
Perasaan itu terakumulasi begitu hebatnya sampai
aku menginjak masa SMP, lalu dengan kenaifan anak usia 15 tahun, aku mencoba
melukai diriku sendiri dengan benda tajam yang guratan bekas lukanya masih ada
sampai saat ini. Saat itu yang kupikirkan hanyalah bagaimana caranya agar
hatiku berhenti merasakan rasa sakit. Aku hanya ingin orang tuaku sadar akan
keberadaanku, lalu menyayangi tanpa tuntutan apapun.
Sekarang, setelah aku memperdalam ilmu
psikologi, khususnya mengenai Psikologi Sosial dan Emosi, aku tahu bahwa
kelekatan yang tidak aman dengan orang tua memang berhubungan dengan
kecenderungan depresi pada usia remaja maupun dewasa awal, lebih spesifiknya
antara usia 15 hingga 20 tahun (Agerup et al., 2015).
Mengacu pada teori pola asuh dari Baumrind,
yang membagi pola asuh ke dalam empat kelompok yakni autoritatif,
authoritarian, permisif, dan pengabaian (Ebrahimi et al., 2017), aku dapat mengatakan kalau aku diasuh dengan tipe authoritarian. Apa itu?
Yakni ketika orang tua mendidik anaknya dengan didikan yang keras, minim oleh
kehangatan, afeksi dan kasih sayang tanpa syarat. Alih-alih, mereka memberikan
tuntutan yang besar pada anak dengan menerapkan aturan dan batasan yang tidak
boleh dilanggar, mereka juga cenderung menerapkan hukuman (Doinita & Maria, 2015).
Tidak mengherankan, ketika remaja, aku
memilih untuk menghindari orang tuaku sendiri dan membangun tembok di antara
kami. Sikap orang tuaku yang seringkali dingin, selalu marah, agresif, bahkan
cenderung memberikan hukuman membuat diriku merasa tidak memiliki tempat untuk
berlindung. Aku merasa sakit hati, frustasi, sedih, ketakutan, cemas dan
kehilangan kepercayaan diri. Dari titik ini aku mulai mengembangkan avoidant
attachment, sebuah tipe kelekatan yang maladaptif dan dikarakteristikkan
dengan rendahnya kedekatan antara anak dan orang tua akibat konflik
interpersonal yang terjadi di antara mereka (Ebrahimi et al., 2017). Akibatnya, anak cenderung menghindari terlibat dengan relasi di
dekatnya, termasuk orang tua dan keluarga yang lain.
Ayah adalah sosok yang sangat mengedepankan
disiplin. Hanya saja, cara beliau menerapkan disiplin saat aku kecil termasuk
keras. Ayah tidak sungkan untuk memukulku ketika aku tidak menurut. Diriku di
masa lalu mungkin akan dendam dan marah pada Ayah karena berlaku demikian.
Namun diriku di masa kini hanya bisa mafhum. Bahwa beliau hanya melakukan apa
yang diyakini beliau benar untuk mendisiplinkanku. Bisa saja akibat didikan
yang beliau terima di masa lalu, bisa juga karena alasan lain yang tidak pernah
bisa kutebak.
Andai saat itu beliau tahu, bahwa dengan
memberikan hukuman fisik pada anaknya seperti memukul atau menendang, memaki,
dan menunjukkan kekecewaan secara berlebihan dapat menuntun pada munculnya
permasalahan pada perkembangan sosial dan emosi anaknya (Grusec et al., 2017). Mungkin agak terlambat bagi beliau untuk menyadari, mengingat sekarang
aku sudah melewati fase tersebut dan telah berusaha menerimanya. Sebagian
gangguan perkembangan emosi pun kurasa masih menetap hingga saat ini, tapi
tidak apa, aku masih punya banyak waktu untuk menyelesaikannya.
Namun, dengan apa yang sudah kupelajari
sejauh ini, aku takkan membiarkan hal yang sama terulang pada adik-adikku.
Aku menyayangi mereka lebih daripada apaun.
Meski dalam beberapa kesempatan, mereka menyebalkan luar biasa. Aku selalu
merasa bahwa aku adalah orang tua kedua mereka setelah Ayah dan Ibu. Aku selalu
berusaha hadir untuk mereka, menjadi pelindung yang sebelumnya tak pernah
kudapat saat masih anak-anak. Aku ingin mendengarkan cerita dari adik-adikku,
baik yang menyenangkan atau tidak. Aku ingin berada dalam segala aspek
kehidupan mereka dan memberikan segala hal yang sebelumnya luput kudapatkan
dari orang tuaku.
Sejauh ini, Ayah sudah tidak pernah menghukum
adik-adikku atau bahkan memukul mereka. Yah, meski beberapa kali aku sempat
mendapati Ayah dan Ibu mengomeli mereka. Ketika kondisi sudah kurasa tidak
mengenakkan, aku selalu menempatkan diri di antara mereka dan mengatakan “Biar
saya aja yang ngomong sama adek”.
Aku tidak ingin adik-adikku mengalami siksaan
emosional seperti diriku dulu. Meski terkadang mereka memang bersalah, aku akan
menegur dengan cara yang takkan menyakiti hati mereka.
Cerita kali ini lumayan panjang, ya? Haha.
Padahal ini belum mencakup semua yang ingin kuceritakan.
Yah, tapi jujur saja. Meski sempat menangis
saat menulis beberapa entri dari blog ini, sekarang aku jauh merasa lebih lega.
Siapa sangka, menyelami diri dapat begitu sangat menguras emosi, namun justru
membuka ruang yang lebih lega di dalam diriku.
Diriku yang lama mungkin tidak pernah menduga
kalau ia akan tumbuh menjadi gadis kuat seperti sekarang. Ia akan tercengang
jika tahu kalau saat dewasa, ia akan mempelajari ilmu psikologi dan juga akan belajar
untuk mengenal dirinya dengan lebih dalam, memaafkan dirinya di masa lalu. Secara khusus, aku sangat bersyukur
karena telah memilih kelas Perkembangan Psikologi Sosial dan Emosi sebagai
kelas peminatan di semester ini. Berkat Bu Novi dan teman-teman di
kelas tersebut, aku belajar bahwa emosi berkembang sejak usia yang sangat dini.
Dipupuk oleh situasi dan perlakuan orang-orang di sekitar kita.
Hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin saja
membuat beberapa aspek dalam perkembangan kita terhambat, namun bukan berarti
bahwa kita akan berhenti untuk berkembang. Justru dari hal-hal tidak
menyenangkan itu, kita seolah diberikan batu loncatan, agar kita dapat mengambil
langkah yang berbeda lalu berkembang dengan lebih baik dari sebelumnya.
Seperti yang saya katakan di awal. Bahagia itu
relatif. Perspektif kita akan kebahagiaanlah yang menentukan sejauh mana kita
merasa pantas atas kebahagian tersebut. Apa yang terjadi di masa lalu, adalah
sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi diriku sekarang.
Sedikit referensi untuk tulisanku kali ini:
Agerup, T., Lydersen, S., Wallander, J., & Sund, A. M.
(2015). Associations Between Parental Attachment and Course of Depression
Between Adolescence and Young Adulthood. Child Psychiatry and Human
Development, 46(4), 632–642.
https://doi.org/10.1007/s10578-014-0506-y
Doinita, N. E., & Maria, N. D. (2015). Attachment and
Parenting Styles. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203,
199–204. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.282
Ebrahimi, L., Amiri, M., Mohamadlou, M., & Rezapur, R.
(2017). Attachment Styles, Parenting Styles, and Depression. International
Journal of Mental Health and Addiction, 15(5), 1064–1068.
https://doi.org/10.1007/s11469-017-9770-y
Grusec, J. E., Danyliuk, T., Kil, H., & O’Neill, D.
(2017). Perspectives on parent discipline and child outcomes. International
Journal of Behavioral Development, 41(4), 465–471.
https://doi.org/10.1177/0165025416681538
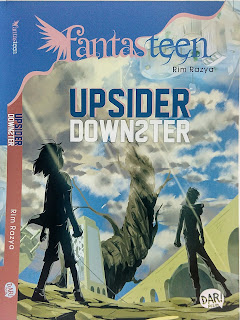
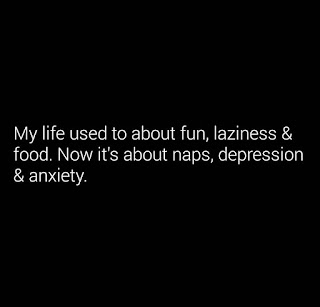
Komentar
Posting Komentar