THE WORST NIGHTMARE
Untuk beberapa kasus, mimpi bukanlah hal yang mesti kukhawatirkan. Namun, pada beberapa kasus lainnya, mimpi adalah satu-satunya jalan keluarku ketika ingin kabur dari kenyataan. Berkat ilmu-ilmu yang kupelajari aku tahu bahwa, mimpi-mimpi merupakan manifestasi dari keinginan yang tidak terpenuhi. Hasrat Ego-mu tidak terpuaskan, tenang, ia akan mendorong hasrat tersebut ke kedalaman alam bawah sadar dan...voila! Terciptalah mimpi.
Tidak selamanya aku menanti-nantikan mimpiku dan menjadikannya shortcut rahasia demi menyingkirkan kecemasan mental. Tidak. Ada saatnya ketika mimpiku bertindak kelewat liar dari yang kuharapkan--bahkan dalam keadaan ekstrem, menjadi mimpi buruk yang paling buruk. Kita semua tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat mengendalikan mimpi, termasuk aku. Dalam kasus ini, sialnya, aku bukan tipe manusia yang mampu mencapai tahap paralysis apalagi lucid dreamer. Jadi, keseluruhan detail mimpiku hari itu menghantamku dengan kerealistisan yang mengerikan. Tanpa bisa kuhentikan, tanpa bisa kuredam.
Kurasa, aku akan selamanya mengingat kengerian mimpi malam itu.
Hari itu, aku tengah memanjakan otak imajinerku dengan membaca novel romance-fantasy karangan Julie Kagawa. Silakan tebak apa judul bukunya jika kalian berminat. Pokoknya, seperti layaknya kutu buku teladan, aku menenggelamkan kepalaku dalam kumpulan kalimat-kalimat yang membius. Singkatnya, buku itu berhasil menarikku 75% lepas dari realita, mengungkungku dalam romance hangat dan pengkhianatan tak terperi. Ada pembantaian, ada pembunuhan, ada darah, tapi harusnya aku sudah terbiasa soal itu. Toh, hei, aku sudah baca The Monstrumologist--cerita tergelap yang mampu kukonsumsi--dan aku tidak bermimpi macam-macam soal kanibal tanpa kepala yang merobek-robek tubuh manusia serta tetek bengek soal usus terburai dsb.
Singkat cerita, tepat sore hari itu satu lagi novel Julie Kagawa tamat olehku. Tidak ada kengerian yang membekas, tidak ada perasaan trauma, hanya perasaan plong yang kurasakan tiap kali menamatkan novel dengan cerita spektakuler. Setelahnya, aku bersikap layaknya....aku. Dengan cengiran konyol dan sejuta fantasi yang bertabrakan di kepalaku. Hal-hal biasa seperti itu...
Tanpa tahu kalau malam itu akan menjadi malam terkelamku.
Aku jatuh tertidur secepat yang mampu ditanggung tubuhku. Aku melepaskan kesadaranku dan merengkuh tabir-tabir ketidaksadaran. Pintu kamar telah kukunci, kipas dinyalakan, selimut menyelimuti separuh tubuhku. Harusnya itu menjadi malam yang sempurna untuk mengisi energi, kan?
Tapi tidak.
Mimpi itu menyergapku bagai berondongan peluru panas. Aku dijatuhkan begitu saja dalam sebuah situasi pasca perang revolusi--karena hanya itu yang mampu kusimpulkan. Berdiri di tengah-tengah gedung bobrok bersama tentara-tentara--yang anehnya--seumuran denganku. Mereka mengenakan rompi anti peluru, helm, dan mengokang senjata laras panjang. Masing-masing tubuh merapat pada dinding gedung, seolah hanya itu harapan mereka demi menghindari gempuran ledakan di luar. Namun ada yang salah.
Setidaknya aku merasa ada yang salah, meski aku tak tahu apa persisnya itu. Aku tidak harusnya berada di sana. Mereka tidak seharusnya berdiri di sana, menyongsong maut yang sudah pasti. Mereka bisa lari, mereka bisa melempar senjata dan mengangkat tangan. Mereka bisa bebas. Semuanya terasa salah.
Kemudian, seseorang yang sebelumnya berjongkok di sisiku bangkit. Ia mengenakan seragam perang seperti yang lainnya. Dia anak laki-laki, tentu saja. Saat itu, wajahnya terpatri jelas dalam benakku. Wajah familier yang selalu datang dalam tiap-tiap mimpiku, wajah yang menjadi aktor-ku. Namun kini, ia hanya berupa seraut wajah buram yang bahkan tak mampu kumunculkan dalam kesadaranku. Aku mengenalnya, tapi juga sekaligus tidak mengenalnya.
Laki-laki itu melepas helmnya dan menimang senjata laras panjangnya. Wajahnya menatap lurus pada rekan-rekannya sementara sebuah sosok muncul di belakangku dan berdiri mendampingi laki-laki itu. Mereka adalah dua orang yang serupa.
(Hal unik dalam mimpiku: aku selalu didampingi oleh dua orang laki-laki dan keduanya kembar. Mereka selalu muncul dalam tiap mimpiku, kebanyakan saat aku tidur dalam kondisi kelelahan. Saat bermimpi, aku mengenal mereka. Saat aku bangun, mereka langsung terlupakan dalam ingatanku.)
Laki-laki yang pertama berbicara pada rekan-rekannya. Lama dan panjang. Intinya, ia berkata kalau mereka tidak harus mengikuti perang ini. Mereka bisa melakukan pembelotan, tidak bakal ada yang tahu. Mereka dapat keluar dari gedung laknat itu hidup-hidup. Dan yang harus mereka lakukan adalah....sialnya...aku lupa.
Singkat kata, anak-anak yang lain meresponnya dengan tawa pasrah. Wajah mereka mendung dan helm anti peluru semakin menggelapkan ekspresi mereka. Saat itu, kami berada di lantai atas--entah lantai berapa--tinggi di atas tanah. Penyerangan digalakkan dari udara dan dari lantai bawah, menyisakan lantai itu sebagai satu-satunya tempat yang aman. Tiba-tiba, setiap anak mengambil posisi di ujung lantai yang tidak memiliki pagar pembatas, menghadirkan akses langsung ke lantai dasar. Posisi strategis jika kalian memilih untuk bunuh diri.
Dan itulah yang terjadi.
Masing-masing anak menyuarakan penolakannya untuk berkhianat seperti yang dianjurkan oleh laki-laki yang pertama tadi. Mereka memilih setia daripada harus menelan pengkhianatan mentah-mentah. Maka, satu per satu anak mengarahkan moncong senjata ke pelipis masing-masing. Saudara kembar laki-laki itu menarikku, menutupi kepala dan pandanganku dengan tangannya, namun tidak bisa menyembunyikan kengerian dari bunuh diri massal itu.
Setiap anak berteriak "Duar!" lalu menarik pelatuk mereka. Terdengar ledakan dan suara tengkorak yang pecah, kibaran seragam perang yang melesat jatuh, tulang-belulang yang patah saat menghantam lantai dasar, koyakan daging yang robek, serta bias darah yang menciprati pilar-pilar serta dinding di belakang mereka. Aku melihat dan mendengar semuanya, berulang-ulang. Lebih dari selusin anak melakukan hal yang sama secara bergantian. Kami bertiga membeku dalam kengerian.
Mimpi tidak pernah terasa lama sekali. Selalu ada pergantian adegan saat adegan yang lain semakin intens. Mimpi takkan pernah selesai tanpa diinterupsi mimpi yang lain. Namun mimpi kali ini lain, aku dipaksa menonton bunuh diri massal itu hingga anak yang paling terakhir. Dipaksa mendengarkan suara-suara memuakkan itu. Dipaksa menonton bertumpuk-tumpuk mayat orang-orang tak berdosa saling tindih dengan banjir darah yang tak pernah kujumpai di kehidupan nyataku. Dipaksa untuk menyerap semua itu tanpa diperbolehkan untuk berpaling.
Mimpiku tidak pernah terasa senyata itu.
Aku terbangun dengan mata melotot, tanpa tarikan napas, tanpa jantung yang berdebar-debar, tanpa keringat yang membanjiri seluruh wajah. Aku terbangun tanpa merasakan apa-apa, dingin menjalari seluruh tungkaiku. Tubuhku kebas, dan yang mampu kuingat hanyalah betapa mengerikannya mimpiku malam itu. Jam menunjukkan pukul 02.05 AM, aku tidak yakin ingin melanjutkan tidurku atau terus melotot membayangkan mimpi itu semalaman. Gambaran itu selamanya terpatri dalam kepalaku. Sampai sekarang.
Dan seperti mimpi-mimpiku sebelumnya, dua orang kembar itu kembali terhapuskan dari ingatanku.
Tidak selamanya aku menanti-nantikan mimpiku dan menjadikannya shortcut rahasia demi menyingkirkan kecemasan mental. Tidak. Ada saatnya ketika mimpiku bertindak kelewat liar dari yang kuharapkan--bahkan dalam keadaan ekstrem, menjadi mimpi buruk yang paling buruk. Kita semua tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat mengendalikan mimpi, termasuk aku. Dalam kasus ini, sialnya, aku bukan tipe manusia yang mampu mencapai tahap paralysis apalagi lucid dreamer. Jadi, keseluruhan detail mimpiku hari itu menghantamku dengan kerealistisan yang mengerikan. Tanpa bisa kuhentikan, tanpa bisa kuredam.
Kurasa, aku akan selamanya mengingat kengerian mimpi malam itu.
Hari itu, aku tengah memanjakan otak imajinerku dengan membaca novel romance-fantasy karangan Julie Kagawa. Silakan tebak apa judul bukunya jika kalian berminat. Pokoknya, seperti layaknya kutu buku teladan, aku menenggelamkan kepalaku dalam kumpulan kalimat-kalimat yang membius. Singkatnya, buku itu berhasil menarikku 75% lepas dari realita, mengungkungku dalam romance hangat dan pengkhianatan tak terperi. Ada pembantaian, ada pembunuhan, ada darah, tapi harusnya aku sudah terbiasa soal itu. Toh, hei, aku sudah baca The Monstrumologist--cerita tergelap yang mampu kukonsumsi--dan aku tidak bermimpi macam-macam soal kanibal tanpa kepala yang merobek-robek tubuh manusia serta tetek bengek soal usus terburai dsb.
Singkat cerita, tepat sore hari itu satu lagi novel Julie Kagawa tamat olehku. Tidak ada kengerian yang membekas, tidak ada perasaan trauma, hanya perasaan plong yang kurasakan tiap kali menamatkan novel dengan cerita spektakuler. Setelahnya, aku bersikap layaknya....aku. Dengan cengiran konyol dan sejuta fantasi yang bertabrakan di kepalaku. Hal-hal biasa seperti itu...
Tanpa tahu kalau malam itu akan menjadi malam terkelamku.
Aku jatuh tertidur secepat yang mampu ditanggung tubuhku. Aku melepaskan kesadaranku dan merengkuh tabir-tabir ketidaksadaran. Pintu kamar telah kukunci, kipas dinyalakan, selimut menyelimuti separuh tubuhku. Harusnya itu menjadi malam yang sempurna untuk mengisi energi, kan?
Tapi tidak.
Mimpi itu menyergapku bagai berondongan peluru panas. Aku dijatuhkan begitu saja dalam sebuah situasi pasca perang revolusi--karena hanya itu yang mampu kusimpulkan. Berdiri di tengah-tengah gedung bobrok bersama tentara-tentara--yang anehnya--seumuran denganku. Mereka mengenakan rompi anti peluru, helm, dan mengokang senjata laras panjang. Masing-masing tubuh merapat pada dinding gedung, seolah hanya itu harapan mereka demi menghindari gempuran ledakan di luar. Namun ada yang salah.
Setidaknya aku merasa ada yang salah, meski aku tak tahu apa persisnya itu. Aku tidak harusnya berada di sana. Mereka tidak seharusnya berdiri di sana, menyongsong maut yang sudah pasti. Mereka bisa lari, mereka bisa melempar senjata dan mengangkat tangan. Mereka bisa bebas. Semuanya terasa salah.
Kemudian, seseorang yang sebelumnya berjongkok di sisiku bangkit. Ia mengenakan seragam perang seperti yang lainnya. Dia anak laki-laki, tentu saja. Saat itu, wajahnya terpatri jelas dalam benakku. Wajah familier yang selalu datang dalam tiap-tiap mimpiku, wajah yang menjadi aktor-ku. Namun kini, ia hanya berupa seraut wajah buram yang bahkan tak mampu kumunculkan dalam kesadaranku. Aku mengenalnya, tapi juga sekaligus tidak mengenalnya.
Laki-laki itu melepas helmnya dan menimang senjata laras panjangnya. Wajahnya menatap lurus pada rekan-rekannya sementara sebuah sosok muncul di belakangku dan berdiri mendampingi laki-laki itu. Mereka adalah dua orang yang serupa.
(Hal unik dalam mimpiku: aku selalu didampingi oleh dua orang laki-laki dan keduanya kembar. Mereka selalu muncul dalam tiap mimpiku, kebanyakan saat aku tidur dalam kondisi kelelahan. Saat bermimpi, aku mengenal mereka. Saat aku bangun, mereka langsung terlupakan dalam ingatanku.)
Laki-laki yang pertama berbicara pada rekan-rekannya. Lama dan panjang. Intinya, ia berkata kalau mereka tidak harus mengikuti perang ini. Mereka bisa melakukan pembelotan, tidak bakal ada yang tahu. Mereka dapat keluar dari gedung laknat itu hidup-hidup. Dan yang harus mereka lakukan adalah....sialnya...aku lupa.
Singkat kata, anak-anak yang lain meresponnya dengan tawa pasrah. Wajah mereka mendung dan helm anti peluru semakin menggelapkan ekspresi mereka. Saat itu, kami berada di lantai atas--entah lantai berapa--tinggi di atas tanah. Penyerangan digalakkan dari udara dan dari lantai bawah, menyisakan lantai itu sebagai satu-satunya tempat yang aman. Tiba-tiba, setiap anak mengambil posisi di ujung lantai yang tidak memiliki pagar pembatas, menghadirkan akses langsung ke lantai dasar. Posisi strategis jika kalian memilih untuk bunuh diri.
Dan itulah yang terjadi.
Masing-masing anak menyuarakan penolakannya untuk berkhianat seperti yang dianjurkan oleh laki-laki yang pertama tadi. Mereka memilih setia daripada harus menelan pengkhianatan mentah-mentah. Maka, satu per satu anak mengarahkan moncong senjata ke pelipis masing-masing. Saudara kembar laki-laki itu menarikku, menutupi kepala dan pandanganku dengan tangannya, namun tidak bisa menyembunyikan kengerian dari bunuh diri massal itu.
Setiap anak berteriak "Duar!" lalu menarik pelatuk mereka. Terdengar ledakan dan suara tengkorak yang pecah, kibaran seragam perang yang melesat jatuh, tulang-belulang yang patah saat menghantam lantai dasar, koyakan daging yang robek, serta bias darah yang menciprati pilar-pilar serta dinding di belakang mereka. Aku melihat dan mendengar semuanya, berulang-ulang. Lebih dari selusin anak melakukan hal yang sama secara bergantian. Kami bertiga membeku dalam kengerian.
Mimpi tidak pernah terasa lama sekali. Selalu ada pergantian adegan saat adegan yang lain semakin intens. Mimpi takkan pernah selesai tanpa diinterupsi mimpi yang lain. Namun mimpi kali ini lain, aku dipaksa menonton bunuh diri massal itu hingga anak yang paling terakhir. Dipaksa mendengarkan suara-suara memuakkan itu. Dipaksa menonton bertumpuk-tumpuk mayat orang-orang tak berdosa saling tindih dengan banjir darah yang tak pernah kujumpai di kehidupan nyataku. Dipaksa untuk menyerap semua itu tanpa diperbolehkan untuk berpaling.
Mimpiku tidak pernah terasa senyata itu.
Aku terbangun dengan mata melotot, tanpa tarikan napas, tanpa jantung yang berdebar-debar, tanpa keringat yang membanjiri seluruh wajah. Aku terbangun tanpa merasakan apa-apa, dingin menjalari seluruh tungkaiku. Tubuhku kebas, dan yang mampu kuingat hanyalah betapa mengerikannya mimpiku malam itu. Jam menunjukkan pukul 02.05 AM, aku tidak yakin ingin melanjutkan tidurku atau terus melotot membayangkan mimpi itu semalaman. Gambaran itu selamanya terpatri dalam kepalaku. Sampai sekarang.
Dan seperti mimpi-mimpiku sebelumnya, dua orang kembar itu kembali terhapuskan dari ingatanku.

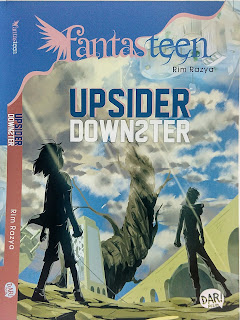

Komentar
Posting Komentar